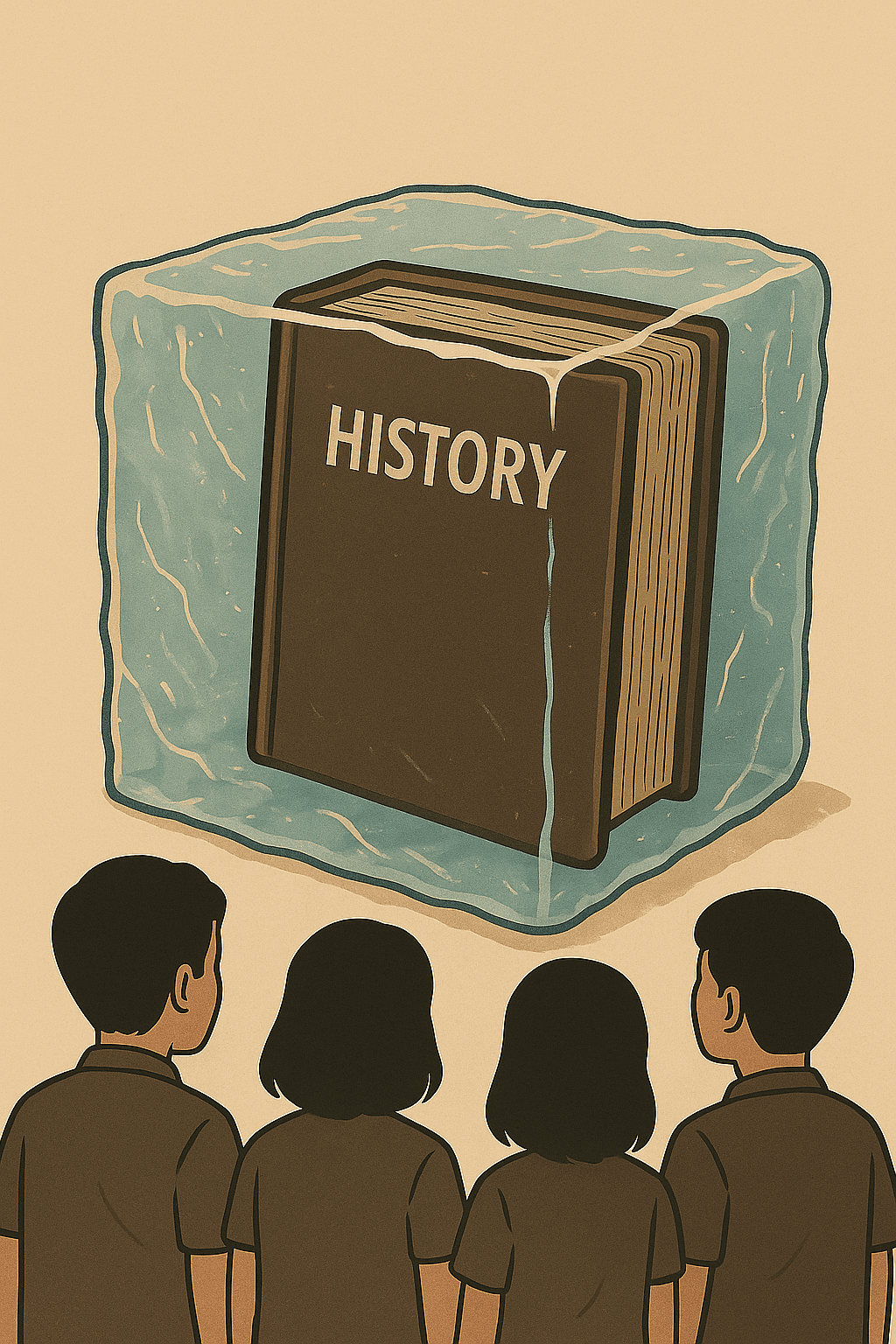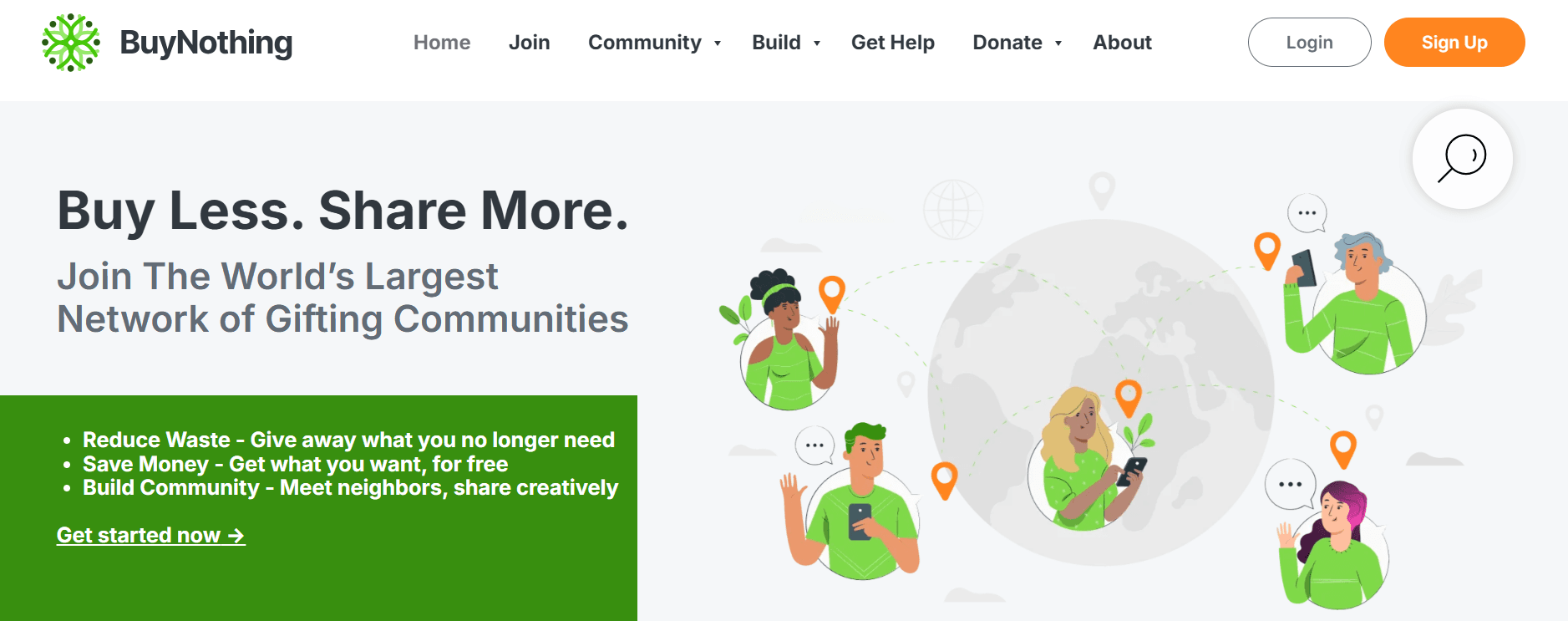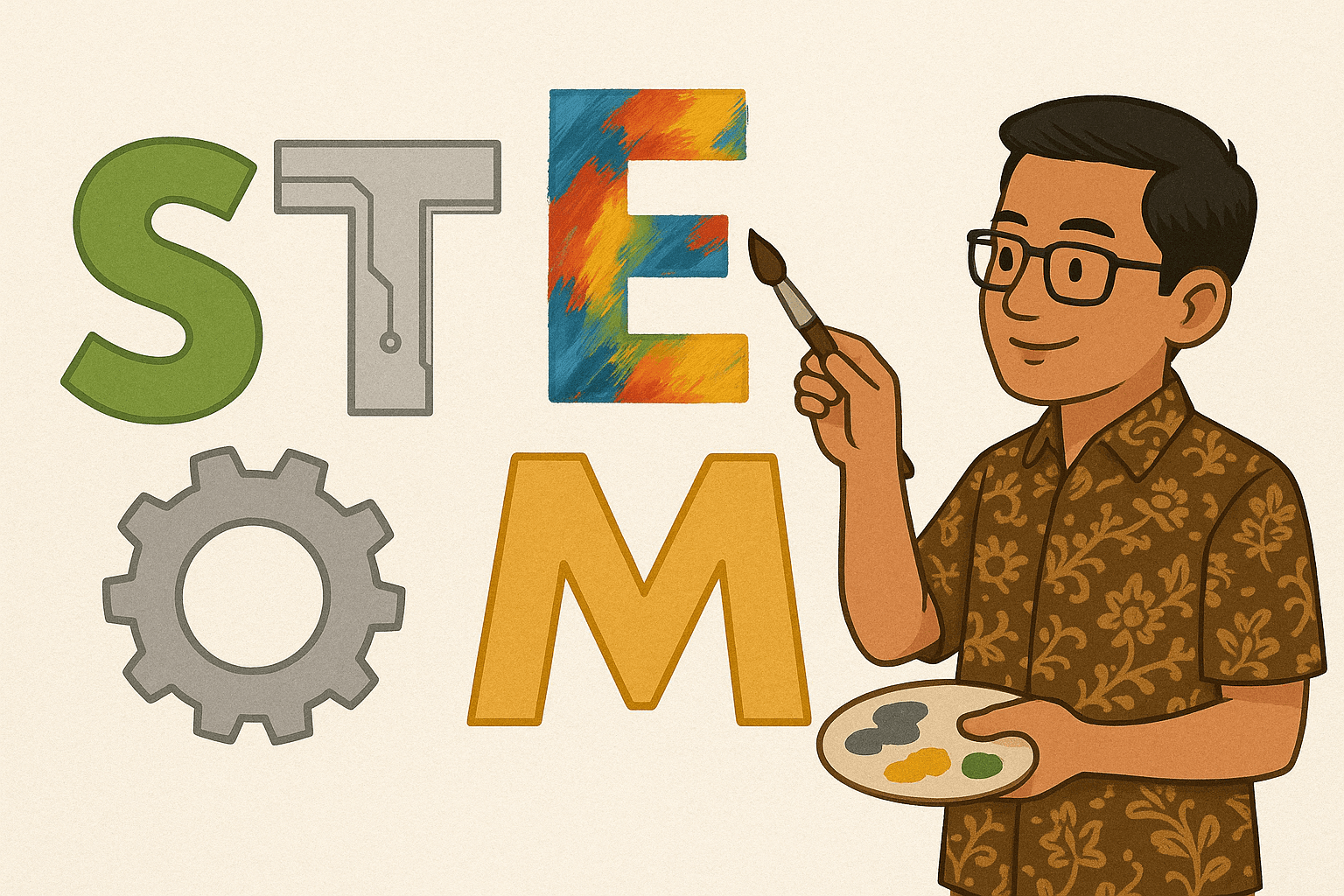Geofragmentasi dan Keamanan Energi: Arah Kebijakan untuk Indonesia
Muhammad Irfan Islami
PhD in Economics at Arndt-Corden Department of Economics, ANU College of Law, Governance and Policy, Crawford School of Public Policy
Email: muhammad.islami@anu.edu.au
Setelah mengalami peningkatan integrasi ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir, dunia kini terancam bahaya Geoeconomic Fragmentation (GEF) yang didorong oleh beberapa kebijakan (Aiyar et al., 2023). Fenomena ini menandai kemungkinan pergeseran struktural dalam tatanan global yang bukan sekadar gangguan sementara. Karakteristik utamanya meliputi berkembangnya tendensi proteksionisme dalam perdagangan, melemahnya atau mundurnya kerja sama multilateral, serta meningkatnya ketegangan dan persaingan geopolitik antarnegara besar. Pendorong di balik tren fragmentasi ini bersifat multifaset dan kompleks. Persaingan strategis antar kekuatan global, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, memiliki peran utama. Persaingan ini dapat memicu berbagai hal seperti konflik dagang, penerapan restriksi teknologi, dan upaya-upaya untuk membentuk blok-blok ekonomi yang lebih terpisah (Gao, 2025). Selain itu, dinamika politik domestik di banyak negara juga memberikan pengaruh besar. Menguatnya arus politik yang berhaluan nasionalis dan populis mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih condong ke dalam negeri (inward-looking). Ditambah lagi, ketidakamanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan kekhawatiran mengenai dampak negatif dari proses globalisasi turut memperkuat dorongan ke arah kebijakan proteksionis.
Manifestasi geofragmentasi terlihat jelas dalam berbagai bidang. Pelemahan Multilateralisme menjadi salah satu ciri utama. Misalnya, kelumpuhan serius Badan Banding (Appellate Body) Organsisasi Perdangan Dunia (WTO) dalam sistem penyelesaian sengketanya sejak 2019 akibat blokade AS (Gao, 2025). Kelumpuhan ini secara efektif menghalangi kemampuan WTO untuk menegakkan aturan perdagangan multilateral dan menyelesaikan sengketa antarnegara anggota. Contoh lain adalah tekanan terhadap komitmen multilateral dalam isu perubahan iklim, seperti penarikan diri AS dari Perjanjian Paris di masa lalu dan tantangan dalam memenuhi pendanaan iklim yang telah dijanjikan (Arbar, 2025). Institusi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengalami tekanan selama pandemi COVID-19, ditandai dengan politisasi, tuduhan keberpihakan, dan munculnya nasionalisme vaksin yang mengutamakan kepentingan domestik di atas solidaritas global (Luc, 2025). Ketegangan Geopolitik yang meningkat, termasuk konflik bersenjata dan persaingan strategis, semakin memperburuk fragmentasi dengan menciptakan ketidakpastian, mengganggu arus perdagangan dan investasi, serta mendorong negara-negara untuk mementingkan keamanan nasional di atas kerja sama ekonomi (Rafitrandi et al., 2024).
Geofragmentasi menimbulkan dampak signifikan pada berbagai aspek sistem global, salah satunya rantai pasok global. Tarif, pembatasan ekspor, sanksi, dan ketidakpastian geopolitik secara keseluruhan meningkatkan biaya produksi, menyebabkan keterlambatan pengiriman, dan memaksa perusahaan untuk memikirkan ulang strategi rantai pasok mereka (Aiyar et al., 2023). Hal ini mendorong munculnya strategi seperti diversifikasi pemasok, reshoring (memindahkan produksi kembali ke negara asal), atau friend-shoring (memindahkan produksi ke negara-negara yang bersekutu secara politik) untuk meningkatkan ketahanan (Mohandas et al., 2024). Selain itu, studi menunjukkan bahwa FDI semakin terkonsentrasi di antara negara-negara yang memiliki kedekatan atau keselarasan geopolitik, terutama untuk investasi di sektor-sektor yang dianggap strategis (International Monetary Fund, 2023).
Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang terbuka dan terintegrasi dalam sistem global, juga dapat terdampak geofragmentasi. Integrasi ini terwujud melalui partisipasi aktif dalam perdagangan internasional, penerimaan FDI, serta keanggotaan dalam berbagai forum multilateral. Perlambatan ekonomi global, ketegangan perdagangan, volatilitas pasar keuangan, dan fluktuasi harga komoditas dapat memengaruhi PDB, neraca perdagangan, nilai tukar, dan stabilitas makroekonomi Indonesia (World Bank, 2024). Industri Indonesia rentan terhadap gangguan rantai pasok global, dan ketidakpastian global dapat memengaruhi iklim investasi serta aliran FDI ke Indonesia, meskipun pemerintah terus berupaya memperbaikinya (Rafitrandi et al., 2024). Integrasi global yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan kini membuat Indonesia sensitif terhadap dampak negatif fragmentasi.
Kerentanan dan Ketergantungan Sektor Energi Indonesia di Era Geofragmentasi
Sektor energi Indonesia memiliki kerentanan inheren yang diperburuk oleh geofragmentasi. Ketergantungan pada impor energi fosil, khususnya minyak mentah (75,72 juta barel pada 2023) dan LPG (sekitar 45% dari total kebutuhan), membuat Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga energi global dan risiko gangguan pasokan akibat peristiwa geopolitik (Fikri, 2024). Selain itu, ketergantungan pada teknologi impor, baik untuk energi konvensional maupun energi baru dan terbarukan, seperti panel surya, turbin angin dan baterai, (Tarumingkeng, 2025) menciptakan kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global, kenaikan harga akibat tarif/perang dagang, dan pengaruh geopolitik negara pemasok. Infrastruktur energi yang tersebar di negara kepulauan juga rentan terhadap bencana alam dan serangan siber (Tarumingkeng, 2025). Ketergantungan pada bahan bakar fosil (fossil fuel lock-in), terutama batu bara, membuat Indonesia sulit beralih ke sumber energi lain dan berisiko merugi karena aset-aset batubara yang tidak terpakai (Giwangkara, 2021). Geofragmentasi memperbesar semua risiko ini, menjadikan ketergantungan impor dan teknologi jauh lebih berbahaya, serta akan berdampak juga terhadap transisi energi di Indonesia.
Akselerasi transisi energi menuju sistem yang lebih bersih dan berkelanjutan membutuhkan investasi dalam skala masif. Berbagai studi dan proyeksi menunjukkan berbagai estimasi besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan transisi energi di Indonesia, mulai dari US$1,177 triliun hingga 2060 untuk 587 GW EBT menurut ESDM/IESR (CASE for Southeast Asia, 2022), hingga US$800 miliar - 1,38 triliun pada 2050 menurut IESR/IRENA (IESR, 2023). Secara tahunan, kebutuhan ini diperkirakan mencapai US$30-40 miliar untuk target NZE 2060. Angka ini kontras tajam dengan investasi aktual EBT yang hanya sekitar US$1,5 - 1,6 miliar per tahun (2021-2023) (Yustika, 2024). Perbedaan besar antara kebutuhan dan realisasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pendanaan (funding gap) yang sangat signifikan. Kesenjangan ini menjadi salah satu hambatan utama percepatan transisi energi, meskipun ada ambisi nasional dan kemitraan internasional.
Tantangan Internal dalam Akselerasi Transisi Energi di Indonesia
Akselerasi transisi energi Indonesia juga terhambat oleh faktor internal.Kebijakan dan Regulasi terhambat oleh inkonsistensi, tumpang tindih, subsidi BBM yang menciptakan persaingan tidak seimbang (Tureah, 2025), regulasi harga EBT yang dinilai tidak layak secara finansial atau bankable di masa lalu (Simanjuntak, 2022), serta ketidakpastian hukum akibat keterlambatan finalisasi RUU EBET dan regulasi pembelian EBT (Paramita & Pranchiska, 2024). Kurangnya koherensi antar kementerian (Paramita & Pranchiska, 2024) dan persyaratan TKDN yang sulit dipenuhi (Yustika, 2024) juga menjadi kendala. Selain itu, terdapat juga tantangan institusional yang berpusat pada peran dominan PLN. Proses pengadaan EBT dinilai tidak teratur dan transparan. Sementara itu, posisi monopoli single buyer dan persyaratan PPA (misalnya, skema mitra wajib dan pembagian risiko yang tidak seimbang) (Tureah, 2025) menghambat investasi swasta (Yustika, 2024). Defisit Infrastruktur seperti jaringan transmisi yang tidak memadai (Tureah, 2025) dan kebutuhan investasi grid strengthening serta energy storage (Colyer & Cory, 2024) menjadi hambatan fisik.
Selain hambatan kebijakan, regulasi, serta infrastruktur, transisi energi di Indonesia juga terhambat karena Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya. Data dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar, mencapai ribuan Gigawatt secara total. Namun, pemanfaatannya secara keseluruhan masih sangat rendah, sehingga hanya mencakup sebagian kecil dari potensi tersebut. Kesenjangan ini terlihat jelas pada berbagai sumber energi, misalnya, pemanfaatan energi surya yang masih minim dan potensi energi laut yang bahkan belum dimanfaatkan sama sekali. Meskipun beberapa sumber seperti hidro dan panas bumi memiliki tingkat pemanfaatan yang relatif lebih tinggi, angkanya masih jauh dibawah potensi sebenarnya. Rendahnya tingkat utilisasi sumber daya EBT ini menjadi tantangan signifikan dalam upaya percepatan transisi energi nasional.
Dampak Geofragmentasi pada Rantai Pasok dan Investasi Energi Terbarukan
Upaya Indonesia untuk mempercepat transisi energi sangat bergantung pada akses terhadap teknologi EBT yang efisien dan terjangkau. Namun, ketergantungan pada impor untuk komponen utama seperti panel surya, inverter, baterai, dan turbin angin (Setiyono, 2024) membuat sektor EBT Indonesia rentan terhadap dinamika geofragmentasi global, terutama persaingan teknologi dan perang dagang antara AS dan Tiongkok. Dampak perang dagang dan restriksi teknologi AS-Tiongkok sangat terasa di sektor EBT, khususnya panel surya. Sejak tahun 2018, AS telah memberlakukan tarif impor yang signifikan terhadap panel surya buatan Tiongkok (Wijaya et al., 2022). Kemudian, tarif tersebut diperluas ke negara-negara Asia Tenggara yang menjadi tempat relokasi perakitan produsen Tiongkok (Sef, 2025). Hal tersebut secara langsung menaikkan biaya komponen bagi proyek PLTS di Indonesia yang mengimpor dari sumber tersebut (Setiawan, 2025). Perang tarif ini juga menciptakan ketidakpastian rantai pasok yang menyulitkan prediksi harga, ketersediaan pasokan, dan perencanaan proyek di Indonesia (Sef, 2025). Meskipun persaingan global dapat menurunkan biaya, fragmentasi dan tarif dapat menetralkan atau membalikkan tren ini, membuat transisi energi lebih mahal dan penuh ketidakpastian bagi pengembang dan pemodal di Indonesia (Yustika, 2024).
Geofragmentasi global ini juga meningkatkan persepsi risiko investor akibat ketidakstabilan rantai pasok, ketidakpastian kebijakan perdagangan, potensi konflik, dan volatilitas pasar (Rafitrandi et al., 2024). Risiko geopolitik cenderung menghambat aliran FDI (International Monetary Fund, 2023), terutama di sektor strategis seperti EBT. Namun, faktor domestik juga memainkan peran krusial. Hambatan internal seperti ketidakpastian kebijakan, proses pengadaan PLN yang rumit, persyaratan PPA yang memberatkan, keterbatasan infrastruktur, dan masalah lahan/perizinan secara signifikan memperparah risiko yang dirasakan investor (Yustika, 2024). Kombinasi risiko eksternal dan internal ini membuat iklim investasi EBT Indonesia kurang menarik dibandingkan pesaing regional, meskipun ada upaya perbaikan dari pemerintah (Yustika, 2024). Perbaikan iklim investasi domestik menjadi sangat penting untuk meredakan dampak negatif geofragmentasi dan mempercepat transisi energi di Indonesia.
Rekomendasi Kebijakan
Indonesia berada pada kondisi krusial dalam perjalanan transisi energi, baik dalam konteks dinamika global maupun kebutuhan domestik yang mendesak. Tantangan perubahan iklim global menuntut pergeseran paradigma dari ketergantungan pada energi fosil menuju sumber-sumber energi bersih dan terbarukan. Secara internal, Indonesia dihadapkan pada urgensi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi volatilitas harga energi akibat fluktuasi pasar global, serta memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagaimana ditekankan dalam berbagai analisis, transisi energi bukan hanya soal perubahan teknologi, tetapi juga memerlukan transformasi sistemik yang didukung oleh kerangka kebijakan yang solid, inovatif, dan terlaksana. Kegagalan dalam mempercepat transisi energi dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam tatanan ekonomi global yang semakin bergeser menuju orientasi keberlanjutan, sekaligus memperbesar kerentanan terhadap krisis iklim dan energi. Oleh karena itu, serangkaian rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terukur mutlak diperlukan. Rekomendasi yang diuraikan dalam laporan ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis yang dapat diterapkan, dengan fokus pada dua pilar utama: penguatan pendanaan domestik untuk mendukung transisi energi (DTE) dan maksimalisasi pemanfaatan energi terbarukan (EBT) lokal. Kedua pilar ini diyakini sebagai fondasi esensial untuk mewujudkan sistem energi nasional yang bersih, berkelanjutan, berkeadilan, dan berketahanan.
1. Peningkatan Pendanaan Dalam Negeri untuk Dukungan Transisi Energi (DTE)
Transisi menuju energi yang berkelanjutan memerlukan investasi finansial yang masif. Ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, seringkali memiliki berbagai persyaratan dan agenda yang mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, optimalisasi seluruh potensi pendanaan dari dalam negeri menjadi sebuah kewajiban strategis untuk memastikan kedaulatan dan keberlanjutan program transisi energi Indonesia.
1.a. Optimalisasi Seluruh Sumber Pendanaan Domestik untuk Transisi Energi
Pendanaan secara domestik bukan hanya tentang mengurangi ketergantungan, tetapi juga tentang membangun kemandirian fiskal dan finansial dalam agenda transisi energi. Strategi ini harus mencakup mobilisasi dana publik melalui APBN dan APBD yang lebih terarah, serta pelibatan sektor swasta domestik secara lebih agresif melalui berbagai instrumen investasi yang inovatif dan menarik.
Analisis terkini menunjukkan adanya kesenjangan pendanaan (financing gap) yang substansial dalam upaya transisi energi Indonesia. Kebutuhan pendanaan tahunan untuk mencapai target dekarbonisasi pada tahun 2050 diperkirakan berkisar antara US$20 miliar hingga US$40 miliar (Anis & Maswan, 2024). Estimasi lain menyebutkan kebutuhan investasi sebesar US$20 miliar hingga US$25 miliar per tahun hingga 2030 untuk mencapai target 100% EBT pada tahun 2050 (IESR, 2022). Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menyoroti adanya potensi kekurangan pendanaan (shortfall) sebesar US$20 miliar.
Namun, realisasi investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) masih jauh dari target. Pada tahun 2023, investasi EBT hanya mencapai US$1,47 miliar. Angka ini masih berada di bawah target Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar US$1,8 miliar untuk tahun yang sama (Anis & Maswan, 2024). Hal tersebut mencerminkan berbagai hambatan struktural dan kurangnya daya tarik investasi di sektor EBT Indonesia. Kegagalan berulang dalam mencapai target investasi tahunan (Anis & Maswan, 2024) menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada aspek-aspek domestik seperti ketidakpastian regulasi, kerumitan birokrasi, kurangnya proyek yang bankable serta tantangan dalam implementasi proyek di lapangan (Anis & Maswan, 2024).
1.b. Penyesuaian Kebijakan Fiskal untuk Peningkatan Penerimaan Negara yang Dialokasikan ke DTE
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pendanaan domestik adalah melalui penyesuaian kebijakan fiskal, khususnya yang terkait dengan sektor ekstraktif. Pendapatan negara dari sektor ini, seperti royalti dan pajak ekspor mineral dan batubara (minerba), dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan untuk DTE jika dikelola dengan tepat. Pemerintah telah mengambil langkah awal dengan menaikkan tarif royalti minerba melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 dan 19 Tahun 2025. Kebijakan ini dipandang sebagai momentum penting untuk mempercepat transisi energi, dengan harapan bahwa dana tambahan yang terkumpul dapat dialokasikan untuk mendukung pencapaian target energi hijau nasional (Pulungan, 2025).
Untuk memperkuat pendanaan domestik dalam menghadapi tantangan transisi energi, direkomendasikan peningkatan pungutan atas produksi batu bara melalui skema royalti yang lebih progresif. Analisis skenario berdasarkan data historis (2019-2023) dari beberapa perusahaan batu bara di Indonesia menunjukkan potensi tambahan penerimaan negara yang sangat signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, dengan harga batu bara yang tinggi, peningkatan tarif royalti dari rata-rata 10,5-12,5% menjadi skema progresif hingga 20-30% berpotensi menambah penerimaan negara lebih dari US$25 miliar dalam satu tahun. Dana substansial yang diperoleh dari optimalisasi royalti ini dapat dialokasikan secara khusus untuk investasi pada proyek-proyek energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta program transisi berkeadilan bagi daerah dan tenaga kerja yang terdampak. Selain optimalisasi royalti, instrumen fiskal lain yang sangat potensial adalah pengenaan pajak ekspor pada komoditas strategis. Sejumlah ekonom dan analis kebijakan telah menyuarakan bahwa pemerintah dapat menerapkan pajak/tarif ekspor pada produk nikel sebagai alternatif untuk meningkatkan penerimaan negara.Tarif ekspor sebesar 10-20% diperkirakan dapat memberikan pemasukan ke negara hingga 100 triliun rupiah (Aswara, 2025).
1.c. Akselerasi Pengembangan Instrumen Investasi Hijau Domestik dan Penarikan Investasi Asing Langsung (FDI)
Selain optimalisasi penerimaan negara, mobilisasi dana swasta, baik domestik maupun asing, juga memegang peran sentral dalam pembiayaan transisi energi. Untuk itu, diperlukan akselerasi pengembangan instrumen investasi hijau di pasar domestik serta upaya proaktif untuk menarik investasi asing langsung (FDI) yang berfokus pada sektor energi terbarukan.
Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mempercepat pengembangan dan penerbitan instrumen seperti obligasi hijau (green bonds), sukuk hijau (green sukuk), dan pinjaman hijau (green loans) oleh berbagai entitas domestik, termasuk pemerintah, BUMN, maupun korporasi swasta. Pasar obligasi hijau global telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi sumber pendanaan penting bagi proyek-proyek berkelanjutan (Climate Bonds Initiative, 2022). Beberapa negara dan lembaga keuangan pembangunan telah sukses dalam memanfaatkan instrumen ini. Sebagai contoh, African Development Bank (AfDB) meluncurkan Green Bond Program yang mendanai inisiatif EBT skala besar di Afrika, dan Afrika Selatan juga berhasil menerbitkan obligasi hijau untuk proyek energi terbarukan dan ketahanan iklim (Financing Africa’s Energy Transition: Innovative Models and Partnerships, 2025).
Meskipun demikian, pasar obligasi hijau domestik di Indonesia sejauh ini dinilai masih kurang menarik bagi investor. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah ketidakpastian terkait insentif fiskal dan non-fiskal bagi penerbit dan investor, status taksonomi hijau Indonesia yang relatif baru dan belum sepenuhnya menjadi bagian dari pasar, serta terbatasnya ketersediaan proyek-proyek EBT yang dianggap bankable atau layak secara finansial (IESR, 2022). Berdasarkan pengalaman Thailand yang berhasil mencatatkan pertumbuhan eksponensial dalam penerbitan obligasi berkelanjutan (mencapai US$8,4 miliar per Oktober 2021), kunci keberhasilannya terletak pada penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment), termasuk keberadaan lembaga peninjau lokal yang kredibel dan platform informasi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang transparan (Climate Bonds Initiative, 2022).
Sejalan dengan pengembangan instrumen investasi hijau domestik, Indonesia juga harus meningkatkan upaya aktif untuk menarik FDI yang secara spesifik menyasar proyek-proyek EBT. Hal ini memerlukan strategi promosi investasi yang lebih terarah, penyederhanaan prosedur perizinan dan investasi, serta penyediaan insentif yang kompetitif dan menarik bagi investor global. Kunci untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing, adalah ketersediaan proyek yang bankable, adanya kepastian regulasi dan hukum, transparansi dalam proses bisnis, serta komitmen terhadap standar perlindungan lingkungan dan sosial yang tinggi (Anis & Maswan, 2024).
2. Memaksimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT) Lokal
Indonesia dianugerahi potensi energi terbarukan yang luar biasa melimpah, mulai dari energi surya, panas bumi, hidro, hingga biomassa dan potensi laut. Namun, pemanfaatan potensi ini masih jauh dari optimal. Memaksimalkan EBT lokal bukan hanya pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk mencapai ketahanan energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2.a. Optimalisasi Potensi EBT Lokal sebagai Kunci Ketahanan Energi
Data potensi EBT Indonesia menunjukkan angka yang fantastis, misalnya potensi energi surya. Namun, realisasi pemanfaatannya masih sangat minim. Kementerian ESDM mencatat potensi teknis sebesar 207.898 MW, sementara IESR menyebutkan potensi teknis yang jauh lebih besar, mencapai 7.714,6 GW atau sekitar 3,4 TW jika digabungkan dengan potensi energi angin (Potensi Energi Terbarukan Di Indonesia, 2025). Kementerian ESDM sendiri memproyeksikan kapasitas terpasang energi surya dapat mencapai 420 GW pada tahun 2060 (Aditya et al., 2025). Namun, hingga akhir tahun 2023, kapasitas terpasang PLTS baru mencapai 573,8 MW (Data Energi Terbarukan, 2024). Meskipun PLN berencana menambah kapasitas PLTS sebesar 4,68 GW pada tahun 2030 (Aditya et al., 2025) dan target RUPTL terbaru mencanangkan tambahan 17 GW dalam dekade berikutnya (Indonesia Targets 35% Renewable Energy Led by Solar, Hydro, Geothermal, 2025), angka-angka ini masih sangat kecil dibandingkan potensinya.
Untuk energi panas bumi, Indonesia diketahui memiliki potensi terbesar di dunia (IESR, 2024). Namun, kapasitas terpasang pada akhir 2023 baru mencapai 2.417,7 MW (Data Energi Terbarukan, 2024), dengan target penambahan dalam RUPTL baru sebesar 5 GW dalam dekade mendatang (Indonesia Targets 35% Renewable Energy Led by Solar, Hydro, Geothermal, 2025). Demikian pula dengan energi hidro, di mana ESDM mencatat potensi hidro dari bendungan sebesar 95.003 MW dan IESR menyebutkan potensi PLTMH sebesar 28,1 GW (Potensi Energi Terbarukan Di Indonesia, 2025). Realisasi kapasitas terpasang PLTA hingga akhir 2023 adalah 6.784,2 MW (Data Energi Terbarukan, 2024), dengan rencana penambahan 16 GW dalam RUPTL baru (Indonesia Targets 35% Renewable Energy Led by Solar, Hydro, Geothermal, 2025). Kesenjangan yang lebar antara potensi dan realisasi ini merupakan indikasi adanya kinerja sistemik yang rendah dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan energi nasional. Hal ini berarti Indonesia menanggung opportunity cost atau biaya peluang yang sangat besar, tidak hanya dalam hal pencapaian target emisi dan ketahanan energi, tetapi juga dalam bentuk potensi penghematan devisa negara (dari pengurangan impor bahan bakar fosil), penciptaan lapangan kerja hijau, dan berbagai manfaat lingkungan lainnya.
Memaksimalkan pemanfaatan potensi EBT lokal adalah strategi pokok untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, baik yang berasal dari impor maupun domestik yang harganya seringkali fluktuatif dan membebani APBN. Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional akan secara langsung meningkatkan ketahanan energi, membantu Indonesia mencapai target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) dalam kerangka Perjanjian Paris, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2.b. Langkah Strategis Mengatasi Hambatan Domestik Pemanfaatan EBT
Untuk membuka potensi EBT lokal, diperlukan serangkaian langkah strategis guna mengatasi berbagai hambatan domestik yang selama ini menjadi kendala utama. Hambatan-hambatan ini meliputi aspek perizinan, kesediaan infrastruktur jaringan, hingga kebijakan harga yang kurang menarik bagi pengembang.
Pertama, penyederhanaan perizinan menjadi prioritas mendesak. Proses perizinan yang panjang, berbelit, dan mahal telah lama menjadi keluhan utama pengembang EBT. Sebuah survei yang dilakukan oleh IESR menunjukkan bahwa 75% pengembang EBT menyatakan bahwa prosedur perizinan memakan waktu yang sangat lama, yang menyebabkan mundurnya jadwal penyelesaian proyek, peningkatan biaya transaksi, dan timbulnya keraguan investor terhadap tingkat pengembalian investasi (IESR, 2022). Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang signifikan mutlak diperlukan untuk memangkas waktu dan biaya perizinan proyek EBT. Pembentukan layanan satu pintu (one-stop service) yang efisien, transparan, dan terintegrasi antar kementerian/lembaga terkait dapat menjadi solusi efektif. Pemerintah juga perlu didorong untuk secara proaktif menyederhanakan seluruh proses perizinan terkait pengembangan EBT.
Kedua, penyiapan infrastruktur jaringan yang memadai. Jaringan transmisi dan distribusi listrik yang ada saat ini sering kali belum siap untuk mengakomodasi pasokan listrik dari sumber EBT yang bersifat variabel dan sporadis (misalnya, surya dan angin). Sistem tenaga listrik nasional saat ini dinilai belum siap untuk penetrasi Variable Renewable Energy (VRE) dalam skala besar karena beberapa faktor, termasuk kondisi kelebihan pasokan listrik di beberapa wilayah (terutama dari PLTU batubara), dominasi PLTU dengan kewajiban serapan minimum (minimum off-take) yang tinggi, serta persyaratan margin cadangan (reserve margin) sistem yang juga tinggi (IESR, 2022). Oleh karena itu, investasi besar dalam modernisasi dan perluasan jaringan transmisi dan distribusi bersifat sangat krusial. Sebagai operator utama sistem ketenagalistrikan nasional, PLN perlu meningkatkan kualitas perencanaan jaringan, memperluas jangkauan jaringan ke wilayah-wilayah potensial EBT, serta mereformasi mekanisme pengadaan untuk mendukung integrasi EBT secara optimal.
Ketiga, kebijakan harga EBT yang menarik dan adil. Kebijakan harga pembelian listrik dari pembangkit EBT menjadi faktor penentu bagi minat investasi di sektor ini. Salah satu penyebab investasi EBT yang stagnan selama ini adalah kurangnya perbaikan dalam lingkungan pendukung investasi, implementasi kebijakan dan kerangka regulasi yang tidak konsisten, penundaan proses pengadaan oleh PLN, serta negosiasi Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL/PPA) yang berlarut-larut (IESR, 2022). Isu harga pembelian listrik juga menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan energi panas bumi (Dwi, 2024). Kebijakan harga harus mampu memberikan kepastian dan tingkat pengembalian investasi yang menarik bagi pengembang, namun tetap mempertimbangkan aspek keterjangkauan tarif bagi konsumen dan kesehatan finansial PLN.
Selain ketiga aspek umum tersebut, perhatian khusus juga diperlukan untuk mengatasi tantangan spesifik di masing-masing sub-sektor EBT. Untuk panas bumi, misalnya, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan iklim investasi, menyelesaikan isu terkait harga listrik, skema kesepakatan bisnis, akses pendanaan, penyempurnaan regulasi, serta pengembangan pasar hilir untuk pemanfaatan langsung panas bumi (Dwi, 2024). Tantangan lain yang signifikan dalam pengembangan panas bumi adalah besarnya investasi awal yang dibutuhkan dan tingginya risiko pada tahap eksplorasi, dimana tingkat keberhasilan sumur eksplorasi seringkali hanya berkisar antara 30-40% (Dwi, 2024).
Berbagai hambatan tersebut saling terkait erat. Proses perizinan yang berlarut-larut akan secara otomatis menaikkan biaya pengembangan proyek, yang pada gilirannya akan menuntut harga jual listrik yang lebih tinggi agar proyek tetap layak secara ekonomi. Di sisi lain, jaringan listrik yang belum siap akan membatasi kapasitas EBT yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem, sekalipun harga yang ditawarkan menarik dan proses perizinan telah disederhanakan. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat parsial atau sektoral tidak akan efektif. Diperlukan sebuah pendekatan yang terkoordinasi dan melibatkan kerjasama lintas kementerian, lembaga, serta BUMN terkait.
2.c. Mendorong Riset, Pengembangan, dan Adaptasi Teknologi EBT Sesuai Kondisi Indonesia
Selain mengatasi hambatan regulasi dan infrastruktur, upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan EBT lokal juga harus didukung oleh penguatan dan pengembangan kapasitas riset atau research and development (R&D) dan adaptasi teknologi EBT yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya EBT yang beragam, namun sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal akibat berbagai kekurangan, salah satunya adalah keterbatasan teknologi yang belum sesuai atau matang secara komersial untuk kondisi lokal.
Investasi dalam R&D dan adaptasi teknologi menjadi krusial untuk memastikan bahwa teknologi EBT yang diadopsi dari luar negeri dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam konteks geografis, iklim, ketersediaan sumber daya alam spesifik, dan kapasitas teknis yang dimiliki Indonesia. PLN sendiri telah mencatatkan kinerja yang positif dalam pengembangan EBT pada tahun 2023 dan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan setiap potensi yang ada (Syofiadi, 2024), namun dorongan untuk R&D yang lebih terarah dan adaptif perlu terus ditingkatkan.
Beberapa area spesifik R&D yang perlu menjadi prioritas antara lain:
Pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage systems), seperti baterai yang efisien, handal, dan terjangkau untuk mengatasi sifat variable dan sporadis dari energi surya dan angin, sehingga dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dari VRE.
Riset pemanfaatan material lokal untuk produksi komponen EBT, misalnya pemanfaatan pasir silika lokal untuk pembuatan sel surya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen impor dan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah TKDN secara kompetitif.
Adaptasi dan pengembangan teknologi PLTS yang sesuai untuk kondisi maritim dan kepulauan, termasuk optimalisasi teknologi PLTS Terapung yang potensinya cukup besar di Indonesia mengingat banyaknya danau dan waduk.
Pengembangan teknologi jaringan pintar (smart grid) dalam berbagai skala, mulai dari skala kecil untuk komunitas terpencil hingga skala besar untuk sistem interkoneksi regional, guna mengoptimalkan integrasi berbagai sumber EBT dan efisiensi sistem.
Riset lanjutan untuk pemanfaatan biomassa dan bioenergi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan teknologi konversi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta memastikan keberlanjutan pasokan bahan baku.
Daftar Pustaka
Aditya, I. A., Wijayanto, T., & Hakam, D. F. (2025). Advancing Renewable Energy in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Challenges, Opportunities, and Strategic Solutions. In Sustainability (Vol. 17, Issue 5). https://doi.org/10.3390/su17052216
Aiyar, S., Ilyina, A., Chen, J., Kangur, A., Trevino, J., Ebeke, C., Gudmundsson, T., Soderberg, G., Schulze, T., Kunaratskul, T., Ruta, M., Garcia-Saltos, R., & Rodriguez, S. (2023). Geo-Economic Fragmentation and the Future of Multilateralism. Staff Discussion Note SDN/2023/001. In International Monetary Fund (Issue 001). https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2023/01/11/Geo-Economic-Fragmentation-and-the-Future-of-Multilateralism-527266
Anis, M. A., & Maswan, P. (2024). Public Finance on Indonesia’s Energy Transition: Implementation Assessment. https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2024/11/Public-Finance-on-Indonesia-Energy-Transition-Implementation-Assessment.pdf
Arbar, T. F. (2025, January 21). Knock! Trump Takes the United States Out of the Paris Climate Agreement. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250121105013-4-604771/tok-trump-bawa-amerika-serikat-keluar-dari-perjanjian-iklim-paris
Aswara, D. (2025). State Revenue Can Increase from Coal and Nickel Export Levy rather than Increasing VAT to 12 Percent. Tempo.Co. https://www.tempo.co/ekonomi/penerimaan-negara-bisa-bertambah-dari-pungutan-ekspor-batu-bara-dan-nikel-daripada-naikkan-ppn-jadi-12-persen-1189064
CASE for Southeast Asia. (2022). G20 Presidency: Funding for energy transition infrastructure through the 'policy derisking' instrument must be prioritized.
Climate Bonds Initiative. (2022). Green Infrastructure Investment Opportunities THAILAND: 2021 REPORT. In Climate Bonds Initiative. https://www.greenfinancelac.org/
Colyer, T., & Cory, S. (2024). Investing in Indonesia’s Energy Transition. Oliver Wyman. https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/oct/investing-in-indonesia-energy-transition.html%0A%0A%0A%0Akalau ini?
Renewable Energy Data. (2024). Renewable Energy Indonesia. https://renewableenergy.id/data-energi-terbarukan/
Dwi, A. (2024). A Series of Opportunities and Challenges for Geothermal Energy in Indonesia, What Are They? Listrikindonesia.Com. https://listrikindonesia.com/detail/14976/deretan-peluang-dan-tantangan-energi-panas-bumi-di-indonesia-apa-saja
Fikri, M. D. Al. (2024, December 2). The Direction of Indonesia's Energy Independence in the Midst of Global Conflicts and Climate Crises. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241202121507-14-592626/arah-kemandirian-energi-ri-di-tengah-konflik-global-dan-krisis-iklim
Financing Africa’s Energy Transition: Innovative Models and Partnerships. (2025). CLG Global. https://clgglobal.com/financing-africas-energy-transition-innovative-models-and-partnerships/
Gao, H. (2025). Four things to watch in global trade policy in 2025. Hinrich Foundation. https://www.hinrichfoundation.com/research/article/trade-policy/four-things-to-watch-in-global-trade-policy-in-2025/
Giwangkara, J. (2021). The Urgency of Renewable Energy Transition in Indonesia. In Kaukus Ekonomi Hijau.
IESR. (2023). Indonesia Energy Transition Outlook 2024: Peaking Indonesia’s Energy Sector Emission by 2030: The Beginning or The End of Energy Transition Promise. In Indonesia Energy Transition Outlook 2024: Vol. 4:2024. www.iesr.or.id
Indonesia targets 35% renewable energy led by solar, hydro, geothermal. (2025). RECCESSARY. https://www.reccessary.com/en/news/id-regulation/indonesia-targets-35-percent-renewable-energy
Institute for Essential Services Reform (IESR). (2022). Indonesia Energy Transition Outlook 2023: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia: Pursuing Energy Security in the Time of Transition. In Essential Concepts of Global Environmental Governance (Vol. 3). https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2024/03/Indonesia-Energy-Transition-Outlook-2023.pdf
Institute for Essential Services Reform (IESR). (2024). Indonesia Energy Transition Outlook 2025: Navigating Indonesia’s Energy Transition at the Crossroads: A Pivotal Moment for Redefining the Future. In Essential Concepts of Global Environmental Governance (Vol. 5).
International Monetary Fund. (2023). World Economic Outlook: A Rocky Recovery. In International Monetary Fund.
Luc. (2025, January 21). Trump Signs Executive Order, United States Leaves WHO. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250121094545-4-604738/trump-teken-perintah-eksekutif-amerika-serikat-keluar-dari-who
Mohandas, S., Gautam, A., Petersen, C., Nzewi, T., & Bailey, R. (2024). The Geopolitics of Supply Chains (Issue August).
Paramita, R., & Pranchiska, I. (2024). Indonesia's energy mix target in 2023 has again missed. State Budget Bulletin, IX(3), 3–7. www.pa3kn.dpr.go.id
Renewable Energy Potential in Indonesia. (2025). Renewable Energy Indonesia. https://renewableenergy.id/potensi-energi-terbarukan-di-indonesia/
Pulungan, M. A. (2025). Increase in Mineral and Mineral Royalties Drives Energy Transition. KabarBursa.Com. https://kabarbursa.com/ekonomi-hijau/125698/kenaikan-royalti-minerba-pacu-transisi-energi
Rafitrandi, D., Hirawan, F. B., Dzakwan, M. H. A., Atje, R., Siregar, R. N., Widiyadi, V. A., Daulay, N., Pramudyantini, E. Q., & Octauno, E. L. (2024). Indonesia Sustainable Trade and Investment Report 2024: Prospects and Challenges of Sustainable Economy Amidst Global Dynamics.
Sef. (2025, April 11). The U.S. and China "Kill Each Other" Attack Crazy Tariffs, What Is the Impact on the World? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250411132304-4-625236/as-china-saling-bunuh-serang-tarif-gila-gilaan-apa-dampak-ke-dunia
Setiawan, F. W. (2025, April 23). 3,500% U.S. Solar Panel Tariff Rocks Southeast Asia! What is Indonesia's strategy? Compassion. https://www.kompasiana.com/feddyws11/680879b7ed6415409061a9f2/tarif-impor-panel-surya-as-hingga-3-500-ancaman-peluang-dan-strategi-global-energi-terbarukan
Setiyono, S. (2024). INCREASING THE USE OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (NRE) TO REALIZE GREEN ECONOMIC RESILIENCE IN INDONESIA.
Simanjuntak, U. (2022). Looking at the Energy Transition Strategy of the Government of Indonesia in 2022. IESR. https://iesr.or.id/menilik-strategi-transisi-energi-pemerintah-indonesia-di-tahun-2022/
Syofiadi, R. (2024). NRE Development Grows Positively in 2023, PLN Records Sustainable Performance. PT PLN (Persero). https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2024/06/pengembangan-ebt-tumbuh-positif-di-2023-pln-catatkan-kinerja-yang-berkelanjutan/
Tarumingkeng, R. C. (2025). Energy Geopolitics in Indonesia: Natural Resources, Energy Security and Impact on Domestic Politics. RUDYCT e-PRESS.
Tureah, G. (2025). The Country of Perpetual Potential: Indonesia’s Barriers in Renewable Energy Transition. Chicago Policy Review. https://chicagopolicyreview.org/2025/02/06/the-country-of-perpetual-potential-indonesias-barriers-in-renewable-energy-transition/
Wijaya, L. I., Zunairoh, Z., Eriandani, R., & Narsa, I. M. (2022). Financial immunity of companies from Indonesian and Shanghai stock exchange during the US-China trade war. Heliyon, 8(2). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08832
World Bank. (2024). Indonesia Economic Prospects: Funding Indonesia’s Vision 2045 (Issue December).
Yustika, M. (2024). Unlocking Indonesia’s Renewable Energy Investment Potential: Challenges and opportunities for accelerating investment in solar and wind power.
Ditulis oleh Directorate of Public Relation and Alumni Network (11/11/2025)